Lebih dari dua puluh tahun berlalu sejak kematian Munir, upaya untuk mencari keadilan tetap terus berlangsung. Orang-orang yang dekat dengannya menyatakan bahwa kepergian Munir tidak membawa rasa benci, melainkan cinta tulus untuk menyelesaikan satu tujuan: pertanggungjawaban pemerintah.
Hadiah terakhir yang diberikan Munir kepada Suciwati dalam perayaan ulang tahun pernikahan mereka adalah tas dan ikat pinggang.
Munir memberikan kedua barang tersebut beberapa saat sebelum ia berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya.
Selama hidupnya, Munir hanya merayakan dua momen hari ulang tahun, kata Suciwati.
Pertama, hari ulang tahun pernikahan mereka. Kedua, hari ulang tahun anak-anaknya. Baik hari ulang tahun dirinya sendiri maupun Suciwati tidak termasuk dalam daftar perayaan.
"Yang ia ingat adalah hari pernikahan kita," kata Suciwati sambil tersenyum.
Saku dan kerudung itu masih disimpan oleh Suciwati hingga kini, demikian pula kenangan-kenangan lain yang tak akan pernah terlupakan olehnya selamanya.
Di bandara, sebelum pesawatnya lepas landas, Munir memeluk Suciwati beserta dua anaknya. Pelukan itu terasa hangat dan erat. Satu kalimat kemudian terucap dari mulut Munir.
"Ia berkata bahwa ia telah menemukan surga," kenang Suciwati.
Mendengar ucapan Munir, Suciwati hanya mampu merasa bahagia. Di dalam hatinya, ia terus-menerus mengucapkan rasa terima kasih atas apa yang Tuhan berikan kepadanya: keluarga kecil dan kasih sayang dari Munir.
Taman yang awalnya tumbuh di dalam jiwa Suciwati dengan bunga-bunga yang mekar tiba-tiba berubah menjadi awan gelap, di mana bunga-bunga itu layu dan mati. Pada akhirnya: mimpi buruk yang tidak pernah ia percayai.
Saat pesawat yang membawa Munir menuju Belanda melewati langit Rumania, racun arsenik telah menyebar ke dalam sistem tubuhnya dan merusaknya.
Munir meninggal dunia.
Sejak saat itu, Suciwati berkomitmen menyelesaikan satu hal.
"Orang yang membunuh suami saya perlu ditemukan," katanya.
Ditunjukkan dan dibawa ke pengadilan.
Harapan hidup tenang di daerah pedesaan
Bagaimana perasaan hidup dan menikah dengan seseorang yang aktif dalam memperjuangkan keadilan dan bersuara keras melawan ketidakadilan?
Suciwati berhenti sejenak, seakan-akan mencoba membuka tirai yang menyembunyikan kenangan demi kenangan bersama suaminya, Munir Said Thalib.
Bagi Suciwati, ia mampu menyesuaikan diri dengan berbagai aspek yang terkait dengan aktivisme yang dijalani Munir. Meskipun demikian, Suciwati menyebut satu hal yang tidak boleh dikompromikan.
Ruang keluarga. Ruang yang dihuni oleh Suciwati beserta dua orang anaknya.
Sibuk apa pun Munir dalam mengadvokasi kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia, Suciwati tetap tidak ingin urusan keluarga menjadi kacau. Waktu yang harus dialokasikan untuk kedua anaknya, menurut Suciwati, harus selalu tersedia.
Komitmen ini telah disetujui ketika pernikahan mereka berlangsung. Munir sangat memahami aturan tersebut.
"Karena [waktu] liburan tiba-tiba muncul keadaan yang memaksa dia untuk berangkat, dia langsung pergi. Jadi, meskipun tengah malam, ketika dia harus pergi, dia tetap pergi," kata Suciwati.
Pada keadaan tersebut, Suciwati meminta Munir mengambil "cuti pengganti" untuk keluarga.
Tujuan kemanusiaan yang terkandung dalam setiap tindakan yang dilakukan Munir, Suciwati mengakui, adalah sesuatu yang sangat mendesak. Suciwati dapat memahami hal ini karena dia juga memiliki hubungan dekat dengan dunia aktivis.
Namun, komitmen di luar pekerjaan tidak boleh diabaikan.
"Maka, saya berpikir bahwa untuk kemanusiaan, apa pun yang bisa kita lakukan, tetapi kita tidak boleh mengabaikan komitmen yang telah dibangun. Kebersamaan itulah yang juga perlu dipertahankan," katanya.
Hidup bersama Munir membuat Suciwati menyadari bahwa "kebersamaan" bukan sekadar kata; itu adalah sebuah tindakan yang bernilai. Terlebih lagi, perjalanan aktivisme Munir sering kali terlibat dalam berbagai hal yang memiliki konsekuensi yang besar.
Bermacam ancaman dan tekanan datang bergantian seperti suara peluru yang menggelegar di sudut-sudut ruangan yang pernah Suciwati bayangkan sunyi dan tenang.
Pada suatu kesempatan, Suciwati mengungkapkan pernah menerima panggilan dari seseorang yang tidak dikenal dan meminta Munir berhenti menjadi aktivis. Ancaman tersebut juga menyentuh keluarga besar yang sebagian besar menyampaikan pesan serupa.
Tekanan semacam itu, tak terhindar, menimbulkan pertanyaan: seberapa jauh aktivisme sosial atau politik mampu memberikan ruang yang aman bagi mereka yang terlibat di dalamnya?
Hati kecil Suciwati tidak menutup kemungkinan mengenai kehidupan di luar dunia aktivisme. Keinginan untuk hidup "biasa saja" seperti kebanyakan orang terkadang muncul dalam pikirannya.
Meskipun demikian, dalam kenyataan yang lain, Suciwati menyadari dengan jelas bahwa dia tidak mampu memaksa Munir untuk berhenti.
"Pada suatu saat [Munir] tidak bisa diperintahkan untuk diam. Tidak bisa. Dalam artian, hal itu sudah menjadi bagian dari sifatnya," kata Suciwati.
Diskusi mengenai kesempatan untuk "pensiun" sebagai aktivis pernah disampaikan oleh Suciwati dan Munir. Jika tidak lagi menjadi aktivis HAM, Munir ingin tinggal di desa, menurut Suciwati.
"Ia ingin menjadi petani dan memiliki lebih banyak waktu untuk menulis," tambah Suciwati.
Suciwati menambahkan bahwa jalan menuju "hidup tenang" khas Munir akan terwujud selama syarat-syaratnya terpenuhi.
"Jika dia hanya sederhana. Jika Indonesia telah menjadi demokratis dan menjunjung hak asasi manusia, dia akan kembali ke kampung halamannya," kata Suciwati.
Dua syarat yang diajukan Munir, menurut Suciwati, sulit tercapai dalam waktu dekat.
Sebelum Munir meninggal, Indonesia sedang mengalami masa peralihan dari pemerintahan Orde Baru. Gelombang ketegangan dan tantangan masih terus berlangsung, termasuk upaya mencari keadilan bagi para korban pelanggaran HAM yang serius.
Suciwati memandang syarat 'pensiun' yang disampaikan Munir sebagai sebuah pernyataan lembut yang menunjukkan bahwa dia tidak akan berhenti dari medan pertarungan yang telah membawanya bertarung sepanjang hidupnya.
Suciwati tidak menganggap Munir bersikap keras kepala. Ia lebih melihat suaminya sebagai sosok yang menghargai nilai dan idealisme.
Bahkan ketika banyak orang meragukan pilihan hidupnya yang sering menghadapi dinding tinggi, Munir tetap setia berada di jalur ini.
Mengapa harus menjadi aktivis jika kesempatan untuk hidup nyaman tersedia luas?
Berapa kali Munir ditawarkan posisi di pemerintahan, menurut Suciwati. Munir, tentu saja, menolaknya.
Bantuan atau dana bantuan dari organisasi donor internasional seringkali hanya berupa formalitas belaka.
Pemberian sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sama sekali tidak dihiraukan oleh Munir.
Suatu hari, Munir menerima penghargaan dari sebuah organisasi asing karena perjuangannya dalam dunia aktivisme.
Penghargaan tersebut diiringi dengan jumlah uang yang, menurut ingatan Suciwati, mencapai ratusan juta rupiah—yang tergolong besar pada masa itu.
"Uang tersebut justru diberikan untuk operasional KontraS, lembaga yang baru saja ia dirikan, dibandingkan kepada keluarganya," kata Suciwati.
Suciwati tidak pernah mengeluh. Ia menyatakan berbagai penolakan Munir terhadap materi semakin memperjelas posisinya; bahwa Munir bukan orang yang mudah dikendalikan melalui uang.
Tapi, saya juga kaget sebagai seorang istri, ya sudah,lah," terang Suciwati, tertawa.
"Saya karena optimis, karena dia orang yang rajin bekerja, dan kami bangga dengan hasil usaha sendiri, jadi [tawaran] hadiah itu biasa saja," tambahnya.
Maka, inilah yang dibuktikan olehnya [Munir], bahwa dia tidakkemaruk [rakus] dengan nilai-nilai duniawi."
Ikan koi di Kota Batu
Mufid Thalib masih gesit bergerak meskipun usianya sudah memasuki usia tujuh puluhan. Ia baru saja tiba dari pasar ketika saya mengunjungi rumahnya di Kota Batu, Jawa Timur. Setiap hari, Mufid sering menghabiskan waktunya untuk berdagang, selain bersenang-senang dengan cucu-cucunya.
Minuman teh panas yang dituangkan ke dalam cangkir berwarna hijau muda memisahkan kami. Mufid menghirup teh tersebut sebelum akhirnya menceritakan tentang adiknya, Munir Said Thalib.
Pertemuan terakhir dengan adiknya terjadi sekitar satu atau dua minggu sebelum ia pergi ke Belanda, Mufid berusaha mengingat. Saat itu, Mufid membantu Munir membersihkan isi rumah di Kota Batu yang akan ditinggalkan.
Saat proses pindah rumah sedang berlangsung, keduanya berbicara mengenai ayam dan ikan koi milik Munir. Adiknya agak cemas tentang nasib hewan peliharaannya itu.
"Kami kalau ngobrolyang biasa saja. Dia [Munir] tidak pernah menyampaikan sesuatu yang berat jika kami [saudara-saudaranya] tidak bertanya," Mufid menjelaskan.
Lalu saya mendengar kabar bahwa Munir telah meninggal.
Berita kematian Munir menggoncang hati Mufid—demikian pula saudara-saudaranya yang lain. Rasa kehilangan menghancurkan pikiran keluarga Munir.
Sebagai anggota keluarga, Munir memiliki hubungan yang dekat dengan saudara kandungnya yang berjumlah tujuh orang. Munir adalah anak keenam dari pasangan pedagang bernama Said Thalib dan Jamilah Umar Thalib.
Said Thalib meninggal dunia ketika anak-anaknya masih sangat muda. Kehilangan ayah memaksa anggota keluarga Thalib bekerja keras untuk mengatasi berbagai kebutuhan. Jabatan sebagai kepala keluarga kemudian diambil alih oleh Mufid dan saudara tertuanya, Rasyid.
Mufid menceritakan bahwa Munir sangat aktif membantu keluarga yang sedang mengalami kesulitan finansial. Misalnya, Munir ikut berdagang sepatu bersama saudara-saudaranya, termasuk Mufid. Di sisi lain, Munir tidak pernah meminta sesuatu yang akan menyulitkan keluarganya.
Keadaan yang disebut Mufid sebagai "penuh keterbatasan" ternyata tidak mengurangi kebahagiaan yang ada dalam diri Munir. Mufid mengingat bahwa ketika Munir masih kecil, ia selalu ceria dan terkenal ramah. Ia memiliki banyak teman.
"Dan saya sendiri tidak tahu bagaimana dia, keahliannya dalam berinteraksi dengan berbagai kalangan itu berasal dari mana. Yang jelas, dia bisa bersosialisasi dengan baik kepada orang lain," jelas Mufid.
Selain anak yang ceria dan mudah beradaptasi, Mufid menganggap adiknya selalu memiliki semangat yang kuat.
Meskipun kondisi keluarganya dianggap kurang memadai dari segi finansial, Munir memiliki semangat besar untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang paling tinggi.
Munir menunjukkan komitmennya dengan menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ia meraih gelar sarjana hukum.
Pemilihan Mufid untuk mengambil studi di bidang hukum dianggap sebagai hal yang istimewa.
Di kalangan keluarga Thalib, Mufid mengatakan, terdapat sosok yang sering menjadi panutan. Nama lengkapnya Mustahar Umar Thalib, seorang dokter di Banyuwangi yang memiliki reputasi baik di masyarakat, salah satunya melalui pendirian rumah sakit.
Kepribadian Mustahar "mempengaruhi saudara-saudaraku," kata Mufid. Muncul keinginan untuk "keluar dari kesulitan hidup" setelah melihat bagaimana Mustahar meraih kesuksesan dalam menjalani profesi dokter.
Kakak dan adik Munir, pada akhirnya, mengikuti jejak Mustahar. Keduanya menjadi dokter. Berbeda dengan keduanya, Munir tidak tertarik.
Ia berlari ke [hukum] studi. Ini adalah pilihan yang telah, menurut kami pada saat itu, menyimpang," kata Mufid diikuti tawa tertawa.
Namun, keluarga tidak melarang Munir untuk mengambil studi hukum, termasuk saat Munir menerapkan ilmu yang ia pelajari dalam kehidupan nyata melalui aktivisme.
"Jelas [terdapat] perasaan bimbang yang tidak bisa kami tolak keberadaannya," Mufid mengakui.
Tetapi, kami juga menyadari bahwa apa yang dilakukan Munir dan kami sebagai keluarga tidak memiliki pilihan lain selain mendukung serta berdoa.
Mufid mengungkapkan secara pribadi "sangat terkejut" dengan keputusan yang diambil oleh Munir. Meskipun ia sendiri sudah lama memperhatikan "tanda-tanda" kepedulian Munir terhadap sesama.
Saat Munir duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, jasad tanpa identitas ditemukan dekat rumah keluarga besar mereka di Kota Batu. Masyarakat mengira korban mengalami gangguan jiwa. Tidak ada yang berani mendekat atau merawatnya, kenang Mufid.
Namun, Munir tidak demikian. Ia pergi ke kantor polisi terdekat dan melaporkan penemuan mayat di pusat kota.
"Saya juga tidak tahu apa yang mendorongnya melakukan hal itu [pergi ke kantor polisi]," jawab Mufid.
Jelas, dari situ, saya akhirnya memikirkan bahwa mungkin sejak dulu sudah ada [kepeduliannya].
Membicarakan 'akar' dari segala sesuatu yang melekat pada Munir, termasuk keberaniannya, sebenarnya, Muhfid menambahkan, berkaitan dengan keberadaan ibunya, Jamilah.
Muhfid mengingat betapa ibunya "telah memberikan ruang yang cukup kepada Munir untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan." Bukan hanya kepada Munir, tetapi anak-anak Jamilah yang lain juga mengalami hal yang sama. Menurut Muhfid, Jamilah tidak pernah memaksakan jalannya hidup bagi anak-anaknya.
Di tengah lorong-lorong panjang yang membatasi realitas keluarga Thalib pada masa itu, Jamilah tetap "kuat dan demokratis," tambah Muhfid.
"Mungkin itu adalah salah satu karakter yang dimainkan oleh Munir," kata Muhfid.
Keyakinan ibunya menjadi seperti panduan untuk menghadapi berbagai tantangan yang turut memengaruhi keluarga besar mereka. Jika ada tuduhan—yang berujung pada serangan—terkait aktivismenya, Muhfid tidak percaya pada perkataan orang lain selain Munir.
"Dulu terkadang dia dianggap cenderung ke [haluan] Kiri. Ada kalanya [dikatakan] cenderung ke [haluan] Kanan. Hal-hal semacam itu yang kami [minta ke Munir] klarifikasi," ujar Muhfid.
Lebih dari dua puluh tahun setelah kematian Munir, Muhfid mengatakan terjadi perubahan pandangan mengenai bagaimana keluarga besar mereka memaknai kasus yang berkaitan dengan Munir.
Mereka memutuskan untuk membatasi diri, kata Muhfid dengan menekankan.
Menurut Muhfid, awalnya kehilangan Munir adalah "hal yang sulit." Kini, mereka telah membuka lembaran baru, memberikan halaman kosong yang akan diisi dengan ketenangan hati.
"Sekarang kami kembalikan kepada masyarakat karena Munir telah menjadi bagian dari sejarah masyarakat. Dengan demikian, publik juga bisa menilai bagaimana seharusnya melanjutkan atau memahami perjuangan Munir di masa lalu," kata Muhfid.
Kami sendiri merasa sudah cukup. Kami telah kehilangan seorang adik, seseorang yang merupakan bagian dari keluarga, dan kami berusaha menerima kepergiannya dengan ikhlas.
Rasa takut yang menghantui di Jalan Diponegoro
Pada malam ketika kabar tentang kematian Munir sampai kepada Usman Hamid, tidak lama kemudian ibunya menghubunginya.
Satu hal yang terus terlintas dalam pikiran Usman: ia pasti diperintahkan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Karena setiap tahun, ibu saya meminta sayaresign dari KontraS," ucap Usman.
Alasannya sederhana: menjadi aktivis pada masa penurunan Soeharto terlalu berbahaya. Mereka yang telah hilang belum menunjukkan nasib yang jelas, dan ibu Usman tidak ingin penderitaan itu menimpa Usman.
Dan ibu saya pernah kehilangan kakak saya, akibat kecelakaan. Dia sepertienggak"ingin kehilangan anak laki-laki lagi," tambah Usman.
Usman telah mempersiapkan diri untuk menyetujui permintaan pengunduran diri dari ibunya. Tidak ada pilihan lain selain itu.
Ternyata Usman salah.
Tidak lama setelah Munir meninggal, ibunya justru mengatakan:
Sekarang kau bawa Ibu ke rumah Munir."
Kemudian kamu carilah siapa yang membunuhnya."
Pada bulan Mei 1998, empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dunia akibat tembakan aparat. Mereka tewas saat terjadi demonstrasi yang menentang pemerintahan Orde Baru. Usman bergabung dengan kelompok mahasiswa yang berupaya mengungkap tindakan represif dari petugas keamanan.
Hari-hari Usman diisi dengan sering mengunjungi sebuah bangunan tua yang terletak di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang menjadi pusat beberapa organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang hukum: KontraS, PBHI, dan YLBHI.
"Itulah tempat saya pertama kali berinteraksi dengan Munir," kenang Usman.
Pertemuan itu meninggalkan kesan yang cukup dalam bagi Usman.
Munir, berdasarkan kesaksian Usman, "sangat jelas dalam menyampaikan pendapat." Pendapatnya mengenai situasi politik setelah jatuhnya Soeharto juga, Usman mengatakan, "mampu melihat keadaan dengan tajam."
Selama bulan Juli hingga Agustus 1998, para mahasiswa masih melakukan demonstrasi meskipun Soeharto telah mundur dari jabatannya. Mahasiswa menganggap pengganti Soeharto, BJ Habibie, memiliki kemiripan dengan Orde Baru, sehingga menimbulkan rasa kecewa.
Di lapangan, teriakan protes mahasiswa bertemu dengan kelompok sipil yang dikumpulkan dalam jumlah yang cukup besar.
"Muinir mampu menjelaskan dengan sangat baik bahwa itu adalah skenario militer untuk menempatkan pihaknya atau kelompok-kelompok perwakilannya dalam bentuk paramiliter atau milisi-milisi guna menghadapi mahasiswa," ujar Usman.
Karena, menurut Munir, mereka [militer] mulai kehilangan pengaruh tertentu.
Kecerdasan Munir tidak membuatnya merasa lebih tinggi dari orang lain.
Munir, Usman mengatakan, tidak pernah meremehkan kemampuan seseorang. Yang dilihat oleh Munir, pertama-tama adalah keinginan.
"Maka, bahkan seorang sopir LBH [Lembaga Bantuan Hukum] yang mendampingi Munir dianggap andalan karena memiliki keberanian, misalnya, dalam mengevakuasi mahasiswa yang diculik atau aktivis yang diburu oleh aparat," lanjut Usman.
Masa Reformasi 1998 dianggap oleh Usman sangat melelahkan. Bila kondisi demikian, Usman cenderung mengambil jeda sebentar untuk meredakan pikirannya. Tempat yang dipilih berada di sekitar Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Di sana, bersama Munir, Usman menikmati hidangan masakan Padang, diikuti dengan agenda berbincang santai.
Pada kesempatan lain, Usman dan Munir sering kali berkendara tanpa tujuan memutari Jakarta. Saat di jalan, jika menemukan warung makan yang sesuai, mereka berhenti. Kali ini, aktivitas makan kuliner tersebut juga diiringi dengan pertukaran pikiran.
Bersama Munir, malam terasa seperti mengalir tanpa henti. Hal ini karena Usman sering diminta untuk merangkum isi percakapan dengan Munir, yang biasanya berlangsung selama beberapa jam, dalam bentuk tulisan.
Yang nulis siapa?
Kamu, lah.
Astaga, tidak tidur, ya, ini.
Pemuda tidak perlu tidur.
Usman hanya bisa tertawa setiap kali kenangan itu muncul dalam pikirannya.
Awalnya tidak saling mengenal, hubungan Usman dan Munir menjadi sangat dekat. Usman melihatnya seperti saudara laki-laki dan perempuan.
Tidak lama setelah lulus dari Universitas Trisakti, Usman sedikit bingung mengenai arah masa depannya. Munir menawarkan padanya untuk bekerja di KontraS yang baru saja didirikan.
Baik, saya akan mengirimkan lamaran nanti.
Astaga, gunakan lamaran apa adanya. Tidak perlu. Langsung masuk saja, lalu bekerja..
Sisi humor yang demikian bukanlah sesuatu yang langka dan sulit ditemukan selama Usman mengenal Munir.
Pada tahun 2002, kantor KontraS yang berada di Jakarta Pusat diserang oleh sekelompok orang yang mengenakan pakaian preman.
Sebelum kejadian tersebut, KontraS sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan keterlibatan seorang jenderal di dalam ABRI—sekarang TNI—dalam kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti.
Beberapa keluarga korban akhirnya memutuskan untuk menggelar aksi unjuk rasa di rumah kediaman Wiranto, yang menjabat sebagai Panglima ABRI saat kekerasan terjadi (1998-1999).
"Maka, menimbulkan sesuatu yang tegang," kata Usman.
Bukan hanya demo, KontraS rencananya akan memanggil Wiranto beserta perwira lainnya.
Kurang lebih seminggu setelah demonstrasi dan rencana pemanggilan tersebut, massa yang diduga terdiri dari preman mengelilingi KontraS. Munir meminta Usman segera menyelamatkan dokumen-dokumen penting.
Masih belum selesai Usman mengatur dokumen, dia mendengar suara kaca yang pecah dengan jelas.
Pyarrr.
Bukan hanya satu, tetapi seluruh kaca yang ada di dalam bangunan.
Pyarrr. Pyarrr. Pyarrr.
Massa kemudian memasuki bagian dalam kantor KontraS. Komputer dirusak. Kursi dan meja dibuang. Suasana sangatchaos.
Anggota KontraS berlari kacau mencari perlindungan, termasuk Usman dan Munir yang berusaha disembunyikan di rumah petugas kebersihan kantor di belakang gedung.
Mereka berlomba melawan waktu karena teriakan kerumunan yang mencari—secara khusus—keduanya sudah tidak bisa lagi ditahan.
Mana Usman?!
Mana Munir?!
Komunis!
Bakar! Bakar!
Saat itu, massa sempat membawa Munir ke tengah ruangan namun kemudian melepaskannya. Setelah seluruh anggota KontraS hancur, massa akhirnya bubar.
Kondisi mulai membaik. Usman menyampaikan isi pikirannya bahwa dia, atau Munir, mungkin saja meninggal dunia akibat amukan massa.
Saat sore hari, seorang teknisi datang ke kantor KontraS. Ia membawa sebuah komputer yang baru.
Munir mendekati orang tersebut. Pandangannya mengamati benda yang beberapa jam sebelumnya hancur dan nyaris tidak tersisa. Sebuah kalimat tiba-tiba keluar dari mulutnya.
Bisa juga, tampaknya ini jika kita diserang. Setiap minggu komputer baru.
"Kami yang berada di sana tertawa mendengarnya," ujar Usman.
Ia selalu menjadi bahan candaan.
Mewariskan jiwa yang luas dan keberanian yang mendukung
Pada suatu hari, putra kedua Munir dan Suciwati meledakkan kemarahannya ketika melihat Pollycarpus Priyanto, orang yang memasukkan arsenik ke dalam tubuh ayahnya, muncul di layar televisi. Suara tangisan keras segera terdengar.
Suciwati tidak berusaha menenangkan dirinya. Ia membiarkan anaknya terjebak dalam perasaan tersebut.
Setelah menangis, Suciwati memeluknya dengan hangat, mengusap air mata yang hampir kering di wajah anaknya.
"Lalu aku bertanya, bagaimana rasanya marah?" kata Suciwati.
"Marah itu melelahkan."
Suciwati menyampaikan kepada putrinya bahwa yang seharusnya diperhatikan bukanlah apa yang terjadi pada Munir, melainkan tindakan yang telah dilakukan oleh Munir.
Benih-benih kebaikan yang terus-menerus disebarkan oleh Munir di lahan yang gersang seperti aliran air yang deras mengalir; memberikan harapan bagi mereka yang hancur akibat ketidakadilan.
"Lalu bekerja dengan penuh kasih, itulah yang memberi kehidupan, dan itu akan bertahan selamanya," kata Suciwati mengulangi perkataan yang pernah ia sampaikan kepada anaknya.
Jika jahat bisa bertahan selamanya, begitu pula dengan kebaikan. Tapi, pilihanmu adalah memilih yang mana?
Pertama kali mendengar berita Munir dibunuh, Suciwati merasa langit tiba-tiba gelap menggantung di atas kepalanya. Perjuangan untuk menemukan keadilan, menurut Suciwati, akan selalu menghadapi dinding tebal di setiap sudut: terjebak dan tidak ada jalan keluar.
Awalnya, Suciwati menambahkan, lembaga negara yang seharusnya melindungi rakyat justru digunakan sebagai alat untuk membunuh.
Pada saat itu, Suciwati sudah memahami bagaimana alur ceritanya akan berjalan.
"Apa maksudnya? Mereka akan melakukan segala hal untuk menyembunyikan kesalahan mereka," tegasnya.
Apakah hal itu kemudian membuat saya diam?
Pertanyaan tersebut dijawab sendiri oleh Suciwati. Lebih dari 20 tahun ia selalu berada di barisan terdepan dalam menuntut pertanggungjawaban negara atas kematian suaminya.
Dari forum resmi hingga Aksi Kamisan, pendirian Suciwati tetap sama: carilah siapa yang ada di balik kematian Munir.
Mahkamah telah menetapkan tersangka terkait kematian Munir. Namun, Suciwati menganggap hal itu belum sepenuhnya membuka kotak tragedi yang melibatkan Munir.
"Ini berkaitan dengan bagaimana mendorong kebenaran, bagaimana mengelola lembaga negara agar dapat digunakan secara tepat, yaitu melindungi warga negaranya, bagi masyarakat sipilnya," jelas Suciwati.
Seringkali Munir dihancurkan melalui label musuh negara dan reputasinya dirusak dengan berbagai cerita yang menyalahkannya—mulai dari agama hingga ideologi.
Segala upaya, menurut Suciwati, berakhir kegagalan, dan akhirnya menggunakan taktik paling terakhir: pembunuhan.
"Mereka hanya terus-menerus menciptakan gangguan agar kami, masyarakat umum, percaya pada perkataan mereka, pada omongan kosong mereka, karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyalahkan Munir," tambah Suciwati.
Suciwati menolak dikatakan membenci negara, serta menyatakan bahwa ia tidak pernah mengandung rasa benci. Selama ini, yang membuat Suciwati bertahan adalah rasa cinta: cinta terhadap Munir dan, yang paling utama, kemanusiaan.
"Apa yang saya lakukan adalah ketika saya tidak ingin ada orang yang dibunuh seperti suami saya, dan pelakunya lepas dari hukuman," tegasnya.
Kematian Munir, menurut Suciwati, bukanlah kematian yang biasa. Terdapat peran pemerintah dalam kejadian tersebut sehingga pantas dimasukkan dalam kategori pelanggaran serius. Secara singkat, negara tidak boleh mengabaikan kasus yang menimpa Munir.
Oleh karena itu, Suciwati tidak akan berhenti dalam perjalanannya untuk mewujudkan apa yang dulu Munir perjuangkan selama hidupnya: keadilan.
Hingga tujuannya benar-benar tercapai, ia hanya memiliki satu pertanyaan yang perlu dijawab.
Apakah kamu membunuh suamiku?
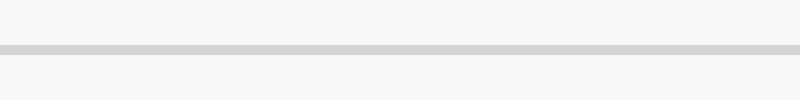
Ini merupakan tulisan pertama dari tiga artikel yang membahas kisah hidup dan wafatnya Munir.
- 21 tahun kematian Munir – Mengapa perkara ini sulit diketahui kebenarannya?
- Munir dibunuh dua dekade yang lalu, putrinya menuntut janji pemerintah – 'Berikan keadilan untuk ayah saya'
- 17 tahun sejak pembunuhan Munir tetapi 'pelaku intelektual' masih belum diketahui
- Tujuh tahun kasus pembunuhan aktivis HAM Munir
- Sepuluh tahun misteri kematian Munir
- Pollycarpus dibebaskan dan menyangkal terlibat dalam pembunuhan Munir, keluarga tetap meminta keadilan
- Pernyataan keluarga korban pembantaian besar-besaran pada tahun 1965-1966 di Bali – 'Jika ayah saya anggota PKI, tetap saja dia tidak pantas dibunuh'
- Penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR dan isu gelar pahlawan nasional, para korban pelanggaran HAM berat: 'Itu merupakan penghinaan. Dia bukan pahlawan tetapi seorang penjahat'
- Laporan Human Rights Watch: Diskriminasi dan pelanggaran rasial terhadap masyarakat Papua "lebih sering dan jelas terlihat" dalam pemerintahan Jokowi
- Keluarga korban penculikan pada tahun 97-98 mengklaim telah menerima 'uang sebesar Rp1 miliar' dari pejabat Gerindra - 'Upaya terstruktur untuk menutup pertanggungjawaban Prabowo'
- Perang di Papua, ribuan penduduk Paniai melarikan diri - 'Roh Kudus, berkatilah kami agar dapat selamat'
- Cerita warga keturunan Tionghoa yang tinggal di luar negeri setelah kerusuhan Mei 1998 dan mereka yang memilih kembali ke Indonesia - 'Semoga pemerintah tidak menghilangkan sejarah'
- Kekacauan Mei 1998: '26 tahun isu kekerasan seksual terhadap perempuan Indonesia ditolak'
- Menelusuri kasus penganiayaan warga sipil oleh anggota TNI di Puncak, Papua – 'Kami bebas melakukan apa saja yang kami inginkan'
- Para peneliti dan aktivis HAM meragukan kenaikan pangkat khusus Prabowo Subianto - 'Ini tidak layak'
